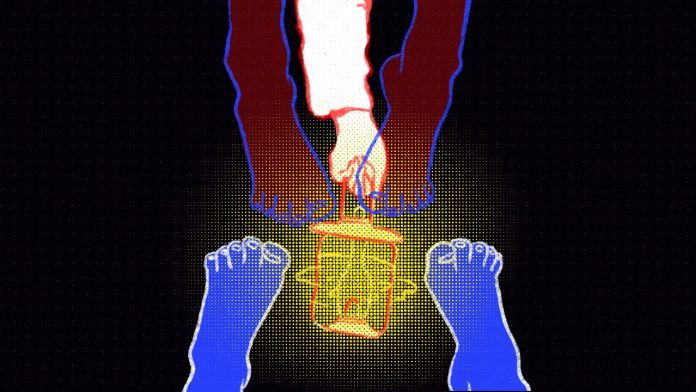Apa yang berikutnya terdengar adalah derap kaki. Derap kaki yang berjalan dengan teratur dan sabar. Derap kaki yang memiliki kuku-kuku tebal dan keras, diikuti suara suit dan gumam gertak, lalu disusul lenguhan-lenguhan. Tak lama, suara kecipak kaki-kaki menyeberangi sungai. Amaqn melihat langit. Masih lama sebelum langgar membunyikan kentongan subuh.
Kali ini memang nahas. Seharusnya sudah ada udang yang makan umpan di kailnya. Suara kecipak air yang tersibak disusul derap kaki memasuki ladang jagung. Daun-daun jagung berkerisik, berebut bunyi dengan genta dan lenguh bersahutan; Tuaq Obet! Hanya Tuaq Obet yang memiliki kerbau paling banyak di Pelambik. Dan pastilah persediaan rumput sudah begitu tipis dan kering sehingga Tuaq Obet harus menyeberangkan kerbau-kerbaunya ke desa tetangga. Amaqn diam-diam menyesali bahwa meski ayahnya seorang kepala guru, mereka tak akan pernah bisa memiliki kerbau seperti Tuaq Obet. Ayahnya terlalu jujur. Mereka hanya punya seekor kuda jantan yang sering dipakai Amaqn latihan menunggang ketika berkhayal menjadi koboi. Dia tidak menjadi koboi, tapi pantatnya babak belur karena kudanya tidak berpelana.
Kandil yang dibawa Amaqn tidak cukup jauh menerangi hingga tengah sungai, tapi ia yakin impan-impan di kail sudah bergerak-gerak. Ia siaga. Kalau udang yang ditangkapnya besar-besar dan banyak, ia yakin Inaqn -istrinya- tidak akan mengomel terlalu panjang karena ia meninggalkan tempat tidur sejak tengah malam. Diambilnya kandil, disorongkan sejauh lengannya memungkinkan. Ia masih tak bisa melihat impan-impan dan ia mengumpat dalam hati. Seharusnya ia tak melupakan senter tadi. Sesekali air sungai menepuki batu-batu di pinggirnya. Amaqn teringat betapa dulu ia sering terpeleset di batu-batu itu.
Kini sungai kembali menghantarkan hening. Lalu Amaqn mendengar suara itu. Pertama samar, lalu semakin jelas. Tapak kaki lagi. Tapak kaki menyeberangi sungai. Hanya saja bukan puluhan derap seperti tadi. Hanya satu suara. Seekor kerbau barangkali tertinggal dan kini menyusul kawanannya. Tapi tapak kaki ini tidak menyeberangi ladang jagung, melainkan bergerak ke arah Amaqn. Ada sebersit cahaya mengikuti, lalu padam. Amaqn menajamkan telinga. Bulu kuduknya meremang. Tidakkah Inaqn pernah berkata ada Bakeq Beraq bersemayam di sungai itu? Amaqn menggeleng kepala, mengusir pikiran itu jauh-jauh. Lalu bunyi tapak itu menjauh, berbelok ke arah gubuk di seberang; gubuk Mamiq Tuan.
“Amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiqq!”
Amaqn yakin teriakan berulang itu bukan imajinasinya. _Bakeq Beraq_ tidak mungkin meneriakkan keterkejutan yang dibungkus kepiluan seperti itu. Teriakan itu menggema di ladang jagung dan memantul-mantul ke sungai.
“Inaaaaaaaaq! Amiq, Inaaaaaaq!”
Panik dan ketergesaan deras mengucur dari teriakan itu. Lalu suara pintu gubuk dihempas, disusul jeritan yang juga memantul-mantul merobek sunyi. Amaqn kini tegak. Ia lupa joran. Ia lupa impan-impan. Ia tajamkan pendengaran. Tapak kaki yang sama, kini berlari. Kecipak sungai tersibak, lalu sepi. Kerbau? Kerbaukah? Pikir Amaqn. Suara tangis dari arah gubuk. Lalu obor-obor bergerak cepat ke arah gubuk Mamiq Tuan. Penduduk telah terbangunkan. Pekik dan seru tertahan di tengah obor-obor.
Debar dada Amaqn jumpalitan. Ia salah. Bukan kerbau yang menyeberangi sungai. Sambil memegangi dadanya, ia mendongak langit. Merah belum muncul, tapi ayam mulai berkokok. Derap kaki lagi. Dari arah yang sama. “Boteq! ”Amaqn mengumpat keras. Sesuatu yang tak seharusnya terjadi telah terjadi. Sesuatu yang seharusnya terjadi, tidak dilakukannya; meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Cahaya obor dan cahaya senter bersiuran ke segala arah. Ada satu cahaya senter yang dibawa berlari mendekati Amaqn lalu berhenti di dekatnya. Pendarnya menerangi sepasang sepatu bot yang mulai usang. Sepatu yang telah menginjak cat warna gelap. Tatapan Amaqn menjajaki sepatu bot itu hingga ke atasnya dan mendapati sepasang celana loreng-loreng. Celana tentara.
Senter itu bergerak ke pundak Amaqn lalu berhenti di wajahnya. Amaqn menutup wajah karena silau.
“Kenapa Saudara di sini?” Suaranya berat, tergesa. Dia tak menggunakan bahasa Sasak tapi logatnya terdengar khas dialek Selatan.
“Tyang mancing, Pak.” Cahaya senter kini menelusuri joran Amaqn. Impan-impan mematuk-matuk liar, lalu diam.
“Hmph. Dapat banyak?” tanya tentara itu. Tapi ia tak menunggu jawaban Amaqn, senternya menyusuri kaleng cat kosong di sebelah Amaqn. “Apa tadi ada lihat seorang lelaki membawa celurit?” tanya si tentara lagi. Senternya kembali menyorot wajah Amaqn. Amaqn mengerjap-ngerjap.
“Tidak ada, Pak. Tyang hanya dengar suara kerbau.” Amaqn terdiam sesaat, lalu melanjutkan, “Tapi memang setelah kerbau-kerbau itu lewat, ada yang jalan menyeberang. Tyang pikir itu kerbau yang tertinggal.”
“Ke arah mana?” desak tentara itu. Amaqn menunjuk ke seberang sungai. Lampu senter dengan cepat menyorot ke arah yang ditunjuk Amaqn.
“Saudara lebih baik pulang,” sambung tentara itu. “Ada yang menyerang Mamiq Tuan. Mungkin yang menyerang masih di sekitar sini. Tidak baik kalau Saudara di sekitar sini.” Amaqn tercekat.
“Astagfirullah, berarti yang tadi menjerit itu…”
Tentara itu mengangguk.
“Anak dan istri Mamiq Tuan. Mereka menemukan Mamiq Tuan tergeletak dengan usus terburai.”
Amaqn menelan ludah. Semua penduduk kampung itu mengenal Mamiq Tuan, pemilik kerbau terbanyak setelah Amaq Obet. Dan semua penduduk kampung sudah tahu cerita bahwa keturunan mereka berdua bermusuhan dan saling membalas dendam kematian keluarga masing-masing. Anak-anak lelaki dan perempuan mereka diajarkan untuk lihai menggunakan senjata. Tidak ada istilah mengibarkan bendera putih. Mereka hanya tahu mata diganti mata, gigi diganti gigi. Wasiat masing-masing keluarga sama. Sebelum mati, mereka akan menyebutkan siapa yang menyerang, dan permintaan untuk membalaskan dendam. Dua bulan lalu, ayah Amaq Obet mati dengan usus terburai.
“Nggih… Nggih, Bapak. Tyang pulang sekarang,” jawab Amaqn tergesa. Ia segera membereskan joran. Tangannya gemetar. Hanya ada satu udang kecil di ujung kail. Inaqn akan mengomel panjang, tapi akan ada kompensasi dari semua ini; Inaqn akan punya cerita untuk digosipkan di pasar sambil berjualan. Desas-desus simpang siur itu kini semakin lezat. Amaqn akan dimaafkan.
Amaqn menjangkau kandil. Nyalanya sudah di ujung sumbu. Kandil itu meredup di dekat si tentara, namun masih menyala sejenak menerangi botnya yang terpercik cat entah di mana. Sekarang Amaqn dapat melihat cat itu berwarna gelap dan basah. Cat berwarna merah.
Darah.
Kandil Amaqn padam.***
Lombok, 12 April 2021
Kosa Kata Sasak:
Impan-impan : pelampung pada kail
Amiq : Ayah
Inaq : Ibu
Boteq : umpatan, secara harfiah berarti monyet.
Tyang : Saya (bahasa halus)
Bakeq Beraq : Makhluk halus
 Julia F. G. Arungan lahir di Lombok, 13 Juli 1982. Merampungkan studi Master di University of South Australia (UniSA), Adelaide. Menulis puisi, cerita pendek, dan naskah drama. Sejumlah puisinya masuk dalam bunga rampai Seratus Penyair Perempuan (KPPI, 2014), Dari Negeri Poci 5: Negeri Langit (Komunitas Radja Ketjil, 2014), Taman Pitanggang (Akarpohon, 2015), dan Ibu (Antologi Kata, 2019). Menulis antologi puisi tunggal ‘Ibuku Mengajari Bagaimana Mengisi Peluru’ (CV Halaman Indonesia dan AkarPohon, 2021). Sekarang bermukim di Sandik, Lombok Barat.
Julia F. G. Arungan lahir di Lombok, 13 Juli 1982. Merampungkan studi Master di University of South Australia (UniSA), Adelaide. Menulis puisi, cerita pendek, dan naskah drama. Sejumlah puisinya masuk dalam bunga rampai Seratus Penyair Perempuan (KPPI, 2014), Dari Negeri Poci 5: Negeri Langit (Komunitas Radja Ketjil, 2014), Taman Pitanggang (Akarpohon, 2015), dan Ibu (Antologi Kata, 2019). Menulis antologi puisi tunggal ‘Ibuku Mengajari Bagaimana Mengisi Peluru’ (CV Halaman Indonesia dan AkarPohon, 2021). Sekarang bermukim di Sandik, Lombok Barat.